selamat datang peziarah digital
Eskatologi Digital: Benang Merah Agama, Filsafat, dan Teknologi Digital
Catatan Pinggir dari Seorang Filosof Receh di Era Akhir Zaman. Di tengah kemacetan informasi dan teriakan digital yang bersahut-sahutan, muncul satu benang merah yang tak pernah putus: keresahan manusia akan akhir. Entah itu akhir zaman, akhir sejarah, atau akhir dari kewarasan. Kita bukan
4/22/20252 min read
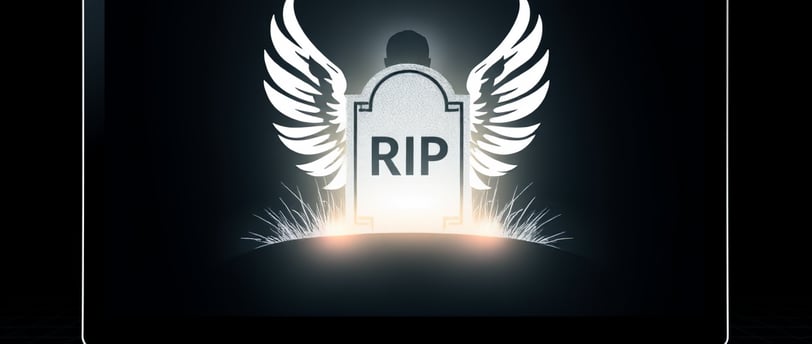

Di tengah derasnya lalu lintas informasi dan gegap gempita jagat digital, ada satu benang merah yang terus muncul dalam diam: kegelisahan manusia pada sesuatu yang berakhir. Entah itu akhir zaman, akhir sejarah, atau sekadar akhir dari kewarasan kolektif.
Kita bukan Harari, bukan Camus, bukan McLuhan. Kita ini generasi pinggiran—filosof receh yang menulis bukan dari podium universitas, melainkan dari tepi ranjang rumah sakit, dari kamar kos sempit, lewat layar yang sudah retak. Tak membawa kitab suci atau teori agung, hanya luka yang menganga, WiFi seadanya, dan segunung tanya yang tak kunjung reda.
Yuval Noah Harari—sejarawan yang lebih kontemplatif daripada teknolog—menulis Sapiens dan Homo Deus untuk menafsir sejarah dan menyeberangkannya ke masa depan digital. Ia mengikat spiritualitas dan data dalam satu simpul yang rapuh namun bermakna.
Lalu ada Reza Aslan, penulis nyentrik tapi tajam, yang membungkus tema agama dalam bahasa pop. Ia membongkar mitos, membuka ruang tanya dalam zaman yang penuh kebenaran palsu.
George Orwell, lewat 1984, tidak memberi ramalan, melainkan cermin. Menyingkap bagaimana bahasa bisa dimanipulasi, realitas dipelintir, dan kebenaran dijadikan alat kekuasaan.
Bahkan Munir Said Thalib—tak menulis best-seller, tapi kematiannya masih menggema hingga kini. Ia mengajarkan kepada kita bahwa keberpihakan kepada yang lemah adalah bentuk spiritualitas yang paling manusiawi.
Tapi kisah tak berhenti di mereka.
Marshall McLuhan menyebut dunia digital sebagai Global Village. Tapi kini, kampung itu riuh, gaduh, dan sering kali saling membungkam. Alvin Toffler, dengan konsep The Third Wave, menangkap perubahan besar bukan sekadar teknologi, tapi juga nilai yang tergerus. Patricia Aburdene menyambungnya dengan membayangkan ekonomi yang tak melupakan sisi ruhani.
Anthony Giddens dan Samuel Huntington menawarkan peta untuk dunia yang sedang retak: antara refleksi modern dan benturan peradaban. Dan jauh sebelumnya, Nietzsche, Camus, Sartre—telah lama menuliskan absurditas, kehampaan, dan pencarian makna dalam dunia yang bungkam.
Jean Baudrillard mungkin yang paling getir. Ia mengabarkan bahwa kita kini hidup dalam salinan dari salinan: realitas yang digantikan oleh ilusi yang lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri.
Di tanah kita, bahkan sebelum ada istilah "eskatologi digital", Jayabaya telah meramalkan zaman edan—di mana yang waras memilih diam dan yang gila duduk di tampuk kuasa. Ronggowarsito tak sekadar menulis tembang; ia membaca tanda-tanda zaman dan memahatnya dalam puisi.
Hari ini, kita juga mendengar suara-suara dari tanah sendiri. Emha Ainun Nadjib—Cak Nun—meramu filsafat jalanan, spiritualitas, dan kritik sosial jadi satu napas. Gus Baha, dengan cara yang jenaka tapi mengena, menghidupkan kembali teks klasik dalam gaya yang membumi dan membelai nalar. Dan Quraish Shihab, sang mufassir terkemuka, menunjukkan bahwa al-Qur'an bukan hanya kitab suci, tapi cahaya yang menembus zaman—menghubungkan wahyu dengan realitas sosial dan politik yang kita jalani.
Semua itu kini tumpah ruah dalam satu layar. Dalam satu sentuhan jempol. Dalam satu scroll yang bisa mengubah hidup, atau sekadar membuat kita lupa arah.
Hari ini, penghakiman tak datang dari langit. Ia muncul dari kolom komentar. Surga dan neraka tak lagi hanya soal keyakinan, tapi juga reputasi digital—yang bisa hancur oleh satu jejak, dan kebaikan yang tenggelam dalam algoritma.
Eskatologi digital bukan sekadar tentang “akhir”. Ia tentang cara baru membaca akhir—dengan filsafat, spiritualitas, dan teknologi sebagai kompas.
Kita sedang menghidupkan kembali peran para pemikir, tapi dengan gaya baru: tanpa harus serius, tanpa gelar, tanpa panggung. Kadang cukup lewat satu meme, satu kalimat yang menggugah, atau artikel seperti ini yang diam-diam merangkul kesepian seseorang.
Filosof receh mungkin tak tercatat dalam buku sejarah. Tapi mereka menyelamatkan hal paling langka hari ini: rasa ingin tahu, nalar yang jernih, dan secuil jiwa yang masih hangat. Dan di zaman yang terus berguncang, itu saja sudah cukup untuk disebut revolusi.
Disclaimer:
Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis yang lahir dari penalaran, renungan, pengalaman serta pengetahuan subjektif penulis. Interpretasi dan kesimpulan yang disajikan bersifat reflektif dan tidak dimaksudkan sebagai jawaban atau kebenaran. Silakan berbeda pendapat dan temukan makna tafsir versi dirimu sendiri
